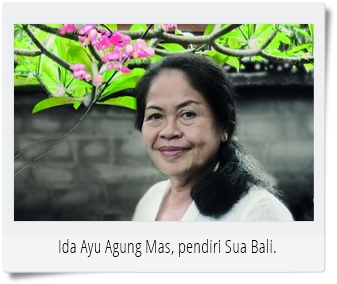Ida Ayu Agung Mas Desakkan ‘Calon Independen’ Di Legislatif
 SEPERCIK kecil isu buram tentang Bali, membuat warga NKRI ikut tersentak dan terluka, terutama yang terkait kedamaian suasana kehidupan. Ketika bom meluluhlantakkan satu sudut tempat di Pulau Dewata tahun 2002, napas kita nyaris terhenti, shock. Irama kehidupan jantung Ibu Pertiwi melemah. Kepariwisataan hancur, rakyat kecil paling menderita dan cukup lama menanggung luka-luka rentetannya. Kepariwisataan Bali memang mempesona dan karena itu amat tersohor. Namun, dari dampak tragedi bom Bali bisa ditarik pelajaran, ternyata “manajemen” kepariwisataan Bali tak kuat di fondasi. Ibarat pohon besar tanpa ditunjang akar yang kuat nan menghujam ke tanah.
SEPERCIK kecil isu buram tentang Bali, membuat warga NKRI ikut tersentak dan terluka, terutama yang terkait kedamaian suasana kehidupan. Ketika bom meluluhlantakkan satu sudut tempat di Pulau Dewata tahun 2002, napas kita nyaris terhenti, shock. Irama kehidupan jantung Ibu Pertiwi melemah. Kepariwisataan hancur, rakyat kecil paling menderita dan cukup lama menanggung luka-luka rentetannya. Kepariwisataan Bali memang mempesona dan karena itu amat tersohor. Namun, dari dampak tragedi bom Bali bisa ditarik pelajaran, ternyata “manajemen” kepariwisataan Bali tak kuat di fondasi. Ibarat pohon besar tanpa ditunjang akar yang kuat nan menghujam ke tanah.
Hal inilah yang lebih 20 tahun lalu sudah diprediksikan Dra. Ida Ayu Agung Mas, pelopor “Sua Bali” atau dikenal dengan Gerakan Pariwisata Inti Rakyat (www.suabali.com).
Ibu dari seorang putera dengan panggilan Gus Krisna, kelahiran Gianyar, kini menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD/MPR) di provinsi Bali, ketika ditemui Koran Tokoh di akhir bulan Februari lalu, baru saja melayangkan surat kepada Ketua DPR RI Agung Laksono. Sedianya Dayu Mas, demikian sapaan sehari-hari Ida Ayu Agung Mas, ingin bertemu langsung dengan pimpinan DPR tersebut.
Inti surat itu mengenai aspirasi masyarakat Bali yang menginginkan agar ‘calon independen’ juga dibahas tuntas dalam sidang paripurna agar bisa diberlakukan segera. Artinya, ‘peraturan pemerintah’ pun segera mengikutinya.
“Karena Pak Agung masih sibuk, saya suruh orang, pokoknya surat saya ini harus sampai ke Pak Agung sebelum Sidang Paripurna DPR RI tanggal 26 (Februari 2008),“ ungkap Dayu Mas.
Aspirasi memunculkan calon independen, menurut dia merupakan green light bagi proses demokrasi. Secara fundamental juga ada niat luhur untuk mendorong perbaikan proses rekrutmen partai politik Selama ini hal itu menjadi kuasa absolut parpol dengan hubungan patronase yang banyak mendistorsi demokrasi politik.
Selain itu, kata Dayu Mas, memperjuangkan calon perorangan merupakan alternatif politik lain. Hal ini harus digulirkan sehingga orbit politik menjangkau mereka yang terpinggirkan.
Siapa yang terpinggirkan? “Perempuan, terutama perempuan Bali,” katanya. Irama zaman, tuntutan global, dan beratnya persoalan tak bisa diatasi tanpa peran nyata perempuan.
Untuk itu, ikatan-ikatan tradisi yang mengungkung, kuasa kelahiran yang kemudian berjalan menyimpang dalam melaksanakan peran yang mengacu pada sistem patriarkat harus dikoreksi dan direvisi. Peran perempuan harus diangkat pula dalam komunitas banjar.
Namun, bagi perempuan Bali untuk ambil peran, menurut Dayu Mas, tidak mudah karena dalam tatanan adat masyarakat Bali, aktor utama dalam struktur adat adalah anak laki-laki, yang dikenal sebagai purusa. Perjuangan sekuat apa pun, hasilnya perempuan tetap di posisi pinggir, kecuali jika dilakukan perombakan.
 Kaum perempuan tidak bisa hanya menanti kapan terjadinya perombakan itu, tetapi harus bergerak untuk memecahkan struktur yang sudah membesi itu agar lebih manusiawi. Berikan peran terhadap perempuan dengan mempertimbangkan hak dan kewajibannya. Misalnya, dimulai dari bagaimana memberi pengertian secara dini pada anak-anak laki-laki maupun perempuan bahwa mereka boleh mempunyai peran berbeda namun hak kelahiran tidak boleh dibedakan.
Kaum perempuan tidak bisa hanya menanti kapan terjadinya perombakan itu, tetapi harus bergerak untuk memecahkan struktur yang sudah membesi itu agar lebih manusiawi. Berikan peran terhadap perempuan dengan mempertimbangkan hak dan kewajibannya. Misalnya, dimulai dari bagaimana memberi pengertian secara dini pada anak-anak laki-laki maupun perempuan bahwa mereka boleh mempunyai peran berbeda namun hak kelahiran tidak boleh dibedakan.
“Ini sebetulnya masalah knowledge, bahwa orang yang menjadi pewaris itu tidak sekadar mewarisi tetapi harus memiliki pengetahuan untuk me-manage warisan itu sesuai perkembangan zaman, sehingga kekayaan warisan itu menjadi produktif bagi anggota keluarga/masyarakatnya.
Warisan yang semestinya dikelola dengan baik itu jangan malah diperebutkan, atau hak-hak bersama yang di Bali dinamakan due tengah yang menjadi milik bersama dijadikan milik individu oleh kelompok atau individu yang karena kelahirannya menjandi pewaris.
Apalagi kalau ranah-ranah publik atau warisan yang seharusnya menjadi milik kelompok suatu generasi dihabiskan sendiri. Bagaimana ajeg Bali bisa berlangsung kalau begini, sementara kekuatan Bali terletak pada pengelolaan manajemen-manajemen kecil yang pada masa lalu cukup kuat, sehingga Bali dinamakan atau mendapat sebutan ‘republik desa’.
“Bali itu seperti republik kecil yang mandiri,” kata seorang anthropolog Belanda. Tanpa wilayah lain di Indonesia, misalnya, Bali bisa eksis. Bali sudah memiliki ajaran tata ruang yang bagus.
Mulai dari Tri Hita Karana (filsafat keseimbangan) sebagai landasan hidup yang dipecah menjadi Tri Mandala yang meliputi ketataruangan yang dimulai dari aturan fisik pekarangan, hingga desa dan kemudian antardesa yang semuanya diatur dengan jelas.
Kemudian ada pula Tri Kaya Parisuda yang merupakan ‘perangkat lunak’ bahwa kita harus berbicara, berpikir, dan berbuat yang benar.
Hukum Rhuwa Bineda/hukum alam seperti berlakunya malam dan siang. Hukum-hukum ini jelas, dijabarkan dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari oleh sebagian besar orang Bali dalam kurun waktu relatif lama. Namun, saat ini hampir semua orang merasakan ada yang berubah, sedang terjadi ketidakseimbangan.
Menurut Dayu Mas, untuk survive dalam kehidupan sehari-hari, perempuan harus berusaha keras untuk bisa berperan dan “tampak’. Jika ingin berperan lebih jauh lagi, diperlukan kemampuan berpikir strategis, seperti dalam dunia politik yang merupakan ruang-ruang yang memerlukan kapasitas itu atau dalam ranah pengambil keputusan.
 Orang yang bisa mencapai tataran berpikir strategis adalah orang yang terlatih berpikir dan memiliki kemerdekaan dan keberanian menyatakan pendapat yang hal itu disebutkan dalam Weda.
Orang yang bisa mencapai tataran berpikir strategis adalah orang yang terlatih berpikir dan memiliki kemerdekaan dan keberanian menyatakan pendapat yang hal itu disebutkan dalam Weda.
Dayu Mas mengakui, perempuan Bali jarang berada di posisi strategis ini karena mereka tidak punya keberanian menyatakan pendapat. Secara jelas adat mengatur bahwa perempuan tidak punya hak suara, termasuk hak suara dalam pasamuan.
Pada masa tertentu zaman dulu mungkin hal itu baik karena situasi zaman menghendaki di mana perempuan harus ditempatkan. Namun, ketika zaman berubah, dan diperlukan orang-orang yang bisa bicara, maka tradisi yang memiliki aturan demikian harus dikaji ulang untuk mengikuti irama zaman.
Sebab, imbas tidak pernah bicara itu sangat besar, dan akhirnya terbukti peran mereka dibutuhkan seperti saat-saat ini para perempuan benar-benar tidak bisa bicara.
Walaupun kaum lelaki secara umum karena alasan yang berbeda tergiring pada situasi tidak mau bicara atau menyatakan pendapat, koh ngomong ini tidak bisa disamakan dengan apa yang menimpa kaum perempuan Bali. Koh ngomong yang dialami masyarakat banyak, telah berdampak jelas.
“Mereka akhirnya terbiasa bicara di luar struktur, seperti di pinggir-pinggir jalan, yang akhirnya bisa menyebabkan terjadi anarkisme,“ katanya. Berbicara terstruktur dengan hak tidak dibiasakan sejak awal.
Itulah yang menyebabkan perempuan ketika harus memasuki ranah politik strategis, bukan politik praktis, ‘hilang’, karena kebiasaan berbicara diberangus dalam pola-pola kehidupan patriarkat yang sebenarnya tidak jelek, namun mengalami penyimpangan.
Hak kelahiran secara tradisi dipahami sebagai kekuasaan. Sebagai yang tertua atau termuda dalam mengelola kekayaan keluarga, hak-hak bersama akhirnya diakui sebagai kekayaan pribadi, seperti menjual tanah atau mengubah kepemilikan tanpa persetujuan anggota keluarga lainnya.
Hak-hak publik yang menjadi milik komunitas juga diselewengkan karena sebagai pemimpin adat atau pemangku merasa punya kewenangan sehinga tanah publik disertifikatkan menjadi tanah milik pribadi, maka hilanglah hak-hak publik.
Realita semacam itu harus disikapi. Apalah artinya segelintir perempuan Bali mampu duduk di posisi strategis jika kenyataan yang terjadi di masyarakat bawah seperti itu. Itu baru satu aspek belum lagi aspek-aspek yang menyangkut sisi kehidupan lain.

Walaupun ada para bapak yang sudah berpikir maju memikirkan anak-anak perempuannya, wacana di ‘kubu’ yang lain juga menguat. Belakangan ada bahkan terjadi dalam suatu dadia bahwa lelaki yang hanya melahirkan anak perempuan akan dicoret dari hak warisnya.
Jadi, menurut Dayu Mas, perempuan sebenarnya tidak hanya diharapkan mampu berperan strategis di lembaga legislatif. Sekarang yang penting harus ada kepedulian terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita, atau harus mampu menyikapi dan mengambil keputusan.
Kebutuhan untuk duduk di parlemen hanya menjadi kebutuhan yang kesekian saja karena permasalahan Bali sekarang ada dalam berbagai tingkat lapisan “Jadi perempuan harus mampu bertindak nyata secara politis maupun praktis, bangkit,“ saran Dayu Mas.
Dalam tataran nasional, kelihatan ada ‘geliat’ kaum perempuan, walaupun gerakan tidak tampak terstruktur dan bahkan tampak sporadis.
Konferensi Beijing telah diratifikasi, undang-undang antipornografi sedang diperdebatkan, sekian banyak pemimpin perempuan mulai muncul di sana-sini, sebagai manejer-manejer perusahaan swasta yang sangat produktif.
Dalam kancah legislasi sedang diupayakan untuk memenangkan affirmative action, untuk memperbanyak jumlah perempuan di parlemen guna mencapai kuota 30% keanggotaan.
Momentum telah tiba. Kaum hawa tidak perlu bersembunyi atau disembunyikan sebagai konco wingking. “Tiap gerakan saya kira mempunyai tujuan yang sama, yaitu ‘menentang sistem yang dominan’,” ujarnya. (dikutip dari Kompas, 3 Maret 2008 – “Quo Vadis Gerakan Perempuan Indonesia”)
Tataran birokrasi pemerintahan sebaiknya juga jangan ketinggalan. Di ruang-ruang ini pun kaum hawa sangat diperlukan terutama dalam posisi pengambil keputusan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Bali sangat kompleks.
Keputusan tidak bisa lagi dipaksakan apalagi diambil dengan pola kekerasan, manipulasi, atau melakukan penekanan. Perempuan bisa mengambil peran karena mereka memiliki kemampuan rekonsilias yang memang menjadi kodratnya.
Kita perlu membangun ‘ruang-ruang gerak yang baru’, yang dilandasi pemahaman bersama bahwa kita sedang memasuki sebuah era baru, ‘era kehidupan berkualitas dan berkeadilan’. Seperti halnya sebuah keluarga yang sedang kedatangan bayi baru, maka tiap anggota keluarga harus mengambil perannya masing-masing tak terkecualikan, menjaga dan membesarkan ‘si jabang bayi’. – isw.
sumber: arixs, 11/3/2008, www.cybertokoh.com
foto > suabali.com + fembooks.de